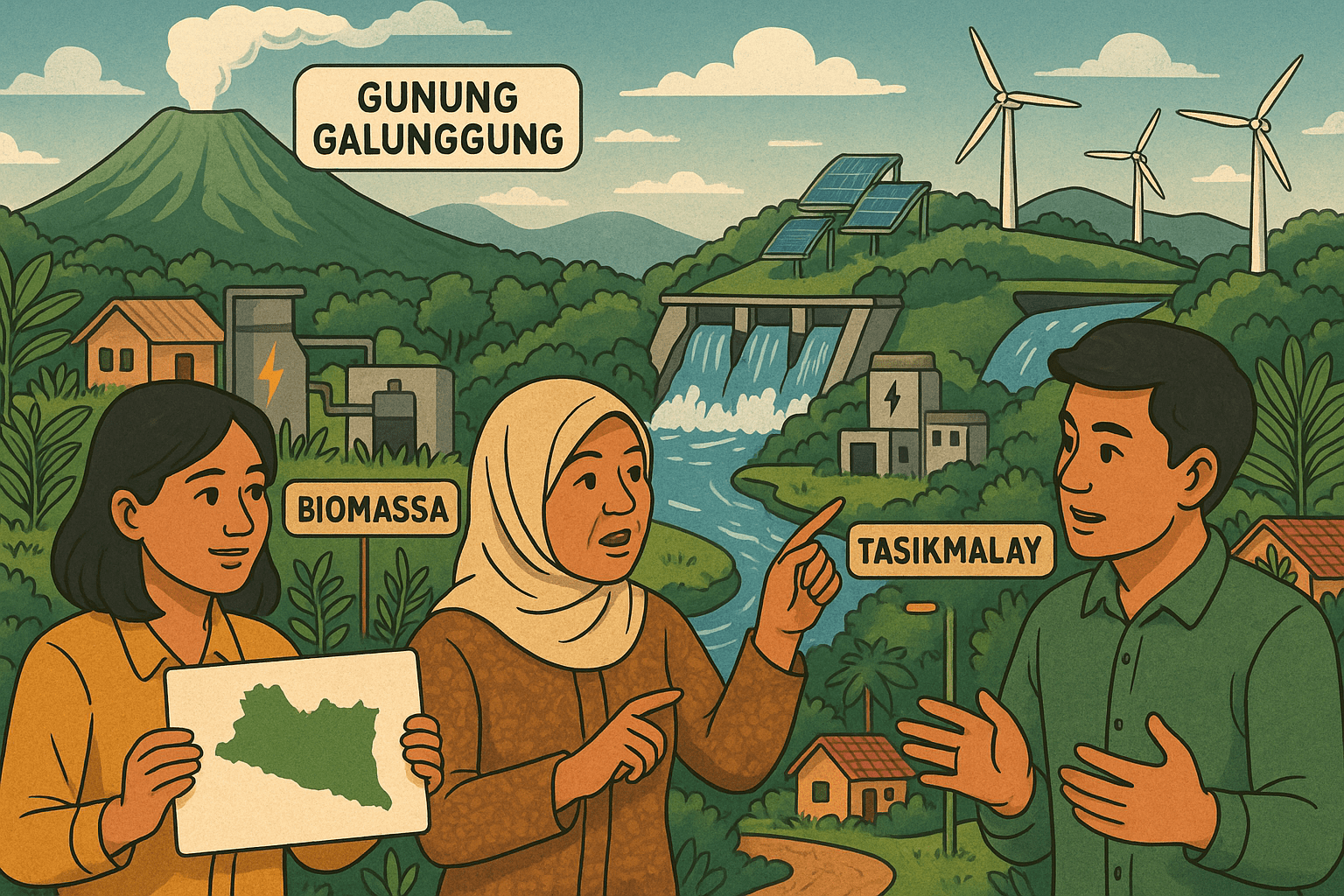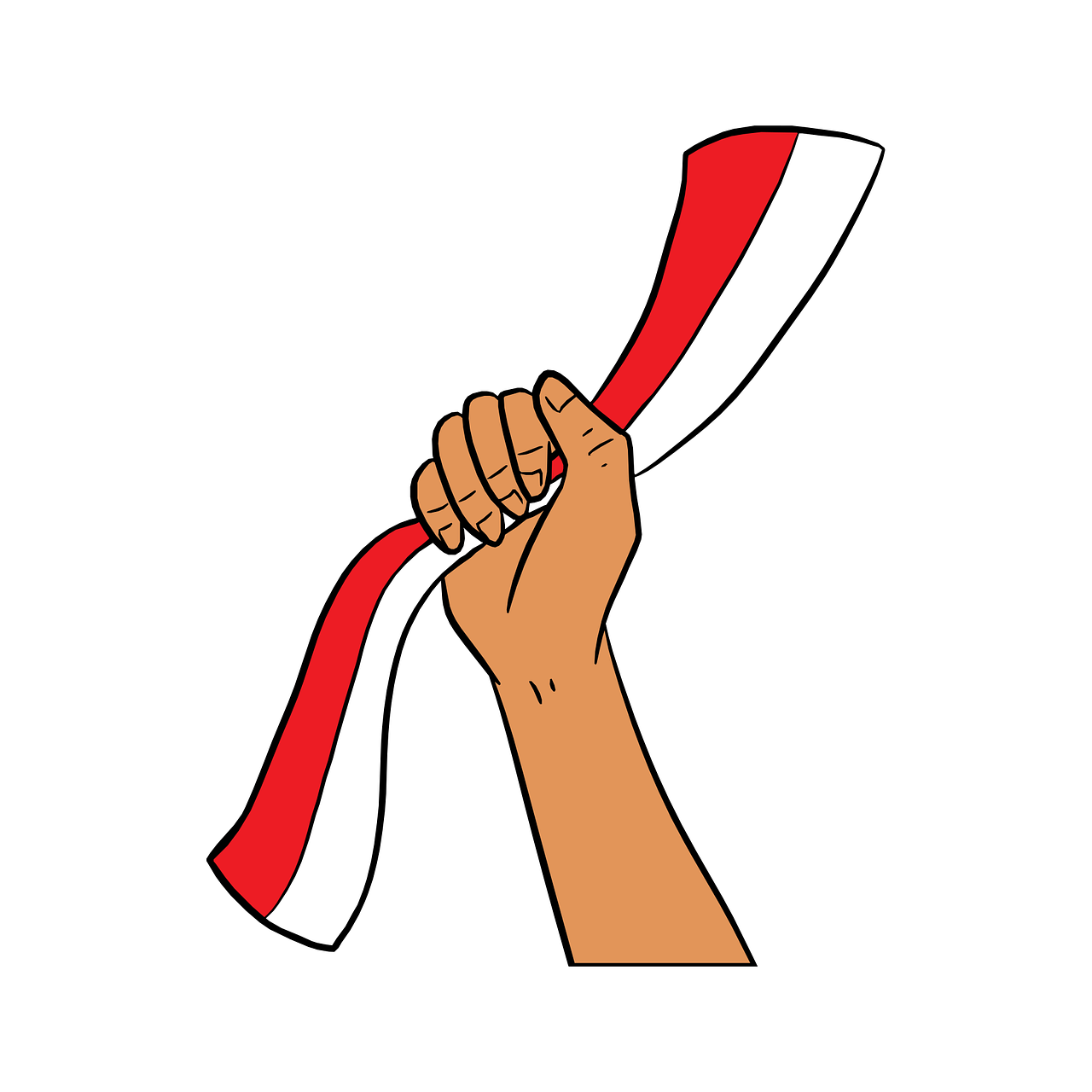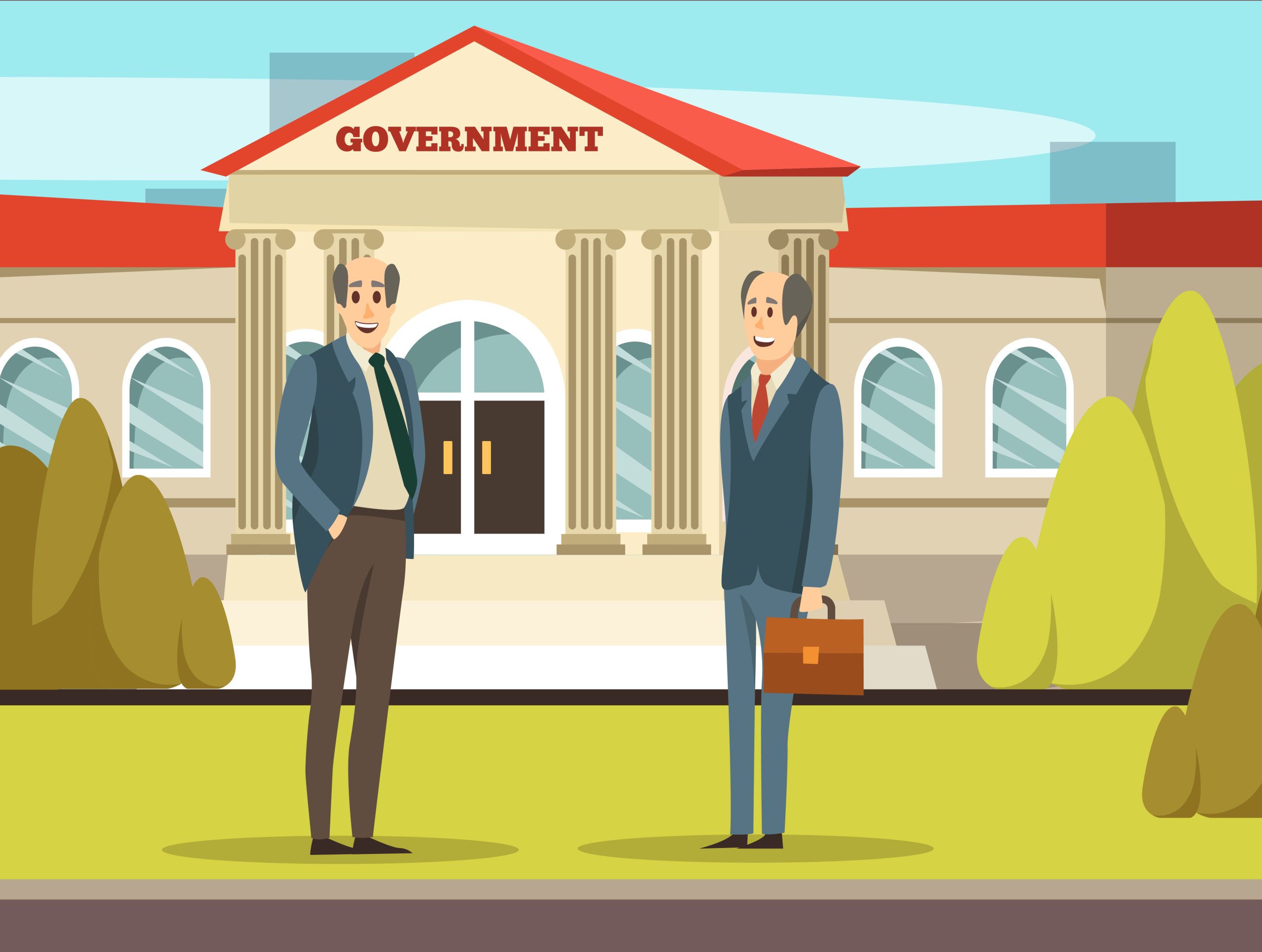
Oleh: Aye Rakhmat Hidayat (Penulis yang juga berprofesi sebagai ASN)
Di negeri ini, “seremoni” telah menjadi semacam agama sekuler. Ia bukan sekadar pelengkap budaya, melainkan nyaris menjelma sebagai jantung aktivitas sosial, politik, bahkan birokrasi. Kita menyukai pemotongan pita, pembukaan resmi, tepuk tangan kolektif, pidato sambutan berantai, potong tumpeng, foto bersama — dan lalu… pulang. Apa yang substansial acapkali tenggelam dalam kemasan. Apa yang esensial sering kali ditenggelamkan oleh formalitas. Budaya seremonial kita begitu mendarah daging hingga tanpa disadari, kita mulai menilai “keberhasilan” dari
seberapa megah panggungnya, bukan dari seberapa besar dampaknya. Padahal dalam banyak kasus, di balik serangkaian ritual resmi itu, tak ada produktivitas yang benar-benar tumbuh. Hanya kelelahan kolektif. Hanya formalitas tanpa roh. Tentu, budaya seremonial bukan sepenuhnya buruk. Ia adalah bagian dari kekayaan sosiokultural bangsa yang menghormati nilai kebersamaan, penghargaan, dan transisi sosial.
Dalam masyarakat agraris, upacara bukan hanya bentuk ekspresi, tapi juga pengikat kolektifitas. Kita mengenal selamatan, ruwatan, mitoni, dan lain sebagainya sebagai bentuk kultural dari penghormatan terhadap siklus hidup. Namun, yang terjadi kini adalah transformasi dari seremoni yang sakral menjadi seremoni yang artifisial. Bukan karena maknanya menguap, tapi karena niatnya tak lagi berakar dari niat luhur. Seremoni modern menjelma jadi ajang eksistensi, show of force kekuasaan, atau malah pengaburan kegagalan struktural. Dari ruang sekolah hingga istana negara, seremoni disulap menjadi teater prestasi, bahkan saat substansi tak pernah benar-benar hadir. Dan kita pun berdamai dengan kenyataan itu. Kita bangga berdiri di balik spanduk besar yang memuat jargon dan logo, meski tak tahu benar apa sebenarnya yang kita rayakan.
Dalam banyak kebudayaan, seremoni adalah bentuk perayaan atas pencapaian. Namun di Indonesia, sering kali ia adalah kompensasi atas kekosongan. Ia menjadi semacam selimut untuk menutupi stagnasi. Maka jangan heran bila kita melihat peresmian gedung yang belum selesai dibangun, seremoni peluncuran program yang tidak pernah jalan, atau deklarasi-deklarasi kosong yang hanya bergema di mikrofon. Kita telah menciptakan kebiasaan unik: menghadirkan harapan dalam bentuk janji-janji panggung dan menandainya dengan prosesi yang mengharukan sebelum semuanya kembali seperti semula. Budaya ini mengasuh generasi muda kita untuk percaya bahwa penampilan lebih penting daripada proses. Bahwa yang penting adalah tampil, bukan bekerja. Maka tak heran jika generasi milenial kita —yang hidup di tengah banjir visual dan simbol — mulai merasa seremonial sebagai bagian dari “kebisingan sosial”. Mereka ikut bertepuk tangan, tersenyum di kamera, menandatangani banner, lalu membuka TikTok dan mulai bertanya dalam hati: apa sebenarnya esensi dari semua ini?
Fenomena ini tak berhenti di ruang sosial, tetapi menjalar hingga ke pusat-pusat kekuasaan. Banyak kebijakan negara yang lebih tampak sebagai panggung retoris daripada aksi nyata. Launching program, sosialisasi, rapat koordinasi nasional, forum diskusi tematik — semua dikemas megah, dengan segala atribut kemegahan. Tapi tak jarang setelahnya, realisasi menguap entah ke mana. Dalam dunia birokrasi, seremoni adalah rutinitas wajib yang terkadang lebih menyita perhatian dan anggaran daripada tindak lanjutnya. Anggaran seremonial dalam beberapa kasus lebih besar daripada program itu sendiri. Rapat dibuka dengan tarian, ditutup dengan nyanyian. Namun tidak ada ruang untuk diskusi mendalam yang menyentuh akar persoalan. Kita sibuk membuat acara, tapi tak sempat mengelola makna. Bahkan evaluasi pun akhirnya menjadi seremoni baru: menghadirkan laporan yang rapi, data yang dipoles, dan tentu — panggung penyerahan plakat.
Generasi Milenial dan Tantangan Autentisitas
Generasi milenial—sering disalahpahami sebagai apatis, padahal sebenarnya jenuh terhadap kepalsuan—membaca ini semua dengan sinis. Mereka hidup di zaman kecepatan, kejujuran, dan pengalaman langsung. Ketika budaya seremoni tak menawarkan kejujuran ataupun pengalaman yang bermakna, maka mereka akan memilih mengabaikannya. Di sisi lain, banyak anak muda yang merasa terpaksa terlibat dalam budaya ini demi kelangsungan karier, relasi sosial, atau tuntutan struktural. Mereka menjadi aktor pasif dalam teater yang mereka sendiri tidak percaya.
Sebuah dilema psikososial yang sangat nyata: bertahan dalam sistem yang tak lagi dipercaya, sambil pura-pura menikmati. Sungguh, ini bukan lagi persoalan gaya atau tradisi, tetapi soal etika sosial. Kita sedang mewariskan budaya kepalsuan kepada generasi yang sesungguhnya menginginkan otentisitas. Generasi yang lapar akan karya nyata, bukan dokumentasi palsu.
Melampaui Kritik: Membangun Budaya Aksi
Namun kritik tanpa arah hanya akan menambah kebisingan. Maka mari kita ajukan satu pertanyaan reflektif: Bagaimana jika kita mulai mengurangi seremoni dan lebih banyak memberi ruang bagi aksi? Bukankah lebih membanggakan bila program pendidikan dimulai tanpa launching megah, tetapi menghasilkan perubahan perilaku nyata? Bukankah lebih sehat bila dana konsumsi acara digeser ke kegiatan yang memberdayakan? Bukankah lebih produktif bila waktu yang dihabiskan untuk sambutan bisa dialihkan ke diskusi yang jujur dan mendalam? Kita tidak anti seremoni. Kita hanya mendambakan seremoni yang bermakna. Yang bukan sekadar panggung, tetapi peristiwa yang memantik kesadaran kolektif. Seremoni seharusnya menjadi penanda perubahan, bukan pelarian dari stagnasi. Ia harus dirayakan ketika ada yang benar-benar patut dirayakan, bukan diadakan hanya demi agenda rutin.
Bagi generasi muda Indonesia, inilah saatnya belajar membedakan antara formalitas dan substansi. Antara impresi dan dampak. Kita tidak hidup untuk selfie di depan backdrop kegiatan, melainkan untuk mewariskan nilai, karya, dan pemikiran. Jika Anda adalah seorang pelajar, mahasiswa, atau profesional muda — mulailah bertanya sebelum terlibat dalam satu acara: “Apa makna dari ini semua?” Jika tidak ada jawaban yang meyakinkan, mungkin sudah waktunya kita berkata: cukup. Kita tidak sedang butuh selebrasi baru, kita butuh kesadaran baru. Kepada para
pemimpin institusi, kepala daerah, pejabat kementerian, bahkan pengurus OSIS sekalipun — mari kita tinjau kembali: apakah kita mengadakan seremoni untuk memberi makna, atau untuk menutupi ketimpangan? Apakah pidato sambutan kita punya daya gerak, atau hanya pengulangan jargon kosong? Mengurangi seremoni bukan berarti melupakan tradisi. Justru dengan merasionalisasinya, kita sedang menjaga makna itu sendiri. Sebab bila terus dipertontonkan tanpa isi, ia hanya akan menjadi parodi — sebuah budaya yang menertawakan dirinya sendiri.
Menuju Ekosistem Produktif dan Otentik
Indonesia adalah negeri yang kaya akan gagasan dan semangat kolektif. Tapi kita terlalu sering menaruh gagasan itu di atas panggung, lalu lupa menurunkannya ke lapangan. Kita terlalu banyak menyapa audiens, tapi jarang menyentuh realitas. Sudah waktunya kita menciptakan ruang-ruang baru yang lebih substansial. Ruang diskusi yang egaliter, forum aksi yang lintas sektor, komunitas yang fokus pada kebermanfaatan konkret. Jangan habiskan energi untuk menjahit dekorasi acara jika kita bisa mulai menjahit harapan masyarakat. Kita tidak sedang melawan seremoni. Kita sedang menata ulang proporsinya. Seremoni bukan musuh, tapi jangan biarkan ia mencuri tempat dari aksi.
Penutup: Renungan di Balik Panggung
Mungkin sudah waktunya kita merenung: seberapa banyak waktu, energi, dan anggaran yang telah kita habiskan hanya untuk memberi ilusi bahwa sesuatu sedang dilakukan, padahal tidak? Dan jika generasi muda tidak belajar mengkritisi budaya ini, maka ia akan mewarisinya tanpa sadar. Menjadi bagian dari sistem yang merayakan kulit, dan melupakan isi. Indonesia bukan kekurangan acara. Tapi kita kekurangan perubahan nyata. Kita bukan miskin seremoni, kita miskin substansi. Dan selama kita terus memilih tepuk tangan daripada kerja nyata, selama itu pula kita hanya menjadi bangsa yang sibuk menciptakan panggung — tapi lupa membangun masa depan.